Tulisan

Ketika belajar menulis esai untuk surat kabar dan dikirim ke sana dengan harap-harap cemas: diterima atau tidak, tulisan ini mengungkap dirinya sebagai sebentuk latihan untuk mengutarakan pikiran, pendapat, bila itu esai dan opini. Atau ungkapan rasa hati dan pengalaman eksistensial hidup, bila itu puisi. Maka antara esai dan puisi, saat-saat bermula belajar sering dikomentari kurangnya daripada lebihnya. “Puisimu kok ‘cengeng’, melankolis dan rentetan ungkapan rasa!” Padahal dalam tahap belajar menulis puisi ini, tolok ukur yang penting adalah kejujuran. Bila yang inti essensi yaitu jujur dan tulus berpuisi, maka yang lain adalah masalah teknis serta how to, meski dalam prosesnya butuh koreksi “obyektif’ dari guru atau orang lain. Inilah guna dan tempat penting mengarang atau menulis artikel di edukasi formal sekolahan khususnya bahasa Indonesia. Tidak apabila kita (dari pengalaman SD, SLTP, SMA) terlalu diberi pelajaran formal tata cara berbahasa Indonesia dan menuliskannya terlalu teknis, seperti aturan SPOK untuk kalimat benar dalam bahasa Indonesia. Ketentuan berkalimat benar adalah subyek: S, predikat yaitu P, ada obyek ialah O dan keterangan atau K. Akibatnya bila ini terlalu ditekankan dan jadi muatan penuh berbahasa, maka tidak ada celah untuk ‘kreasi menulis’ dicelah-celah S.P.O.K ini.
Saya beruntung mendapatkan guru-guru bagus mengarang dan berbahasa tulis ini, yang seimbang antara kalimatnya harus benar, namun diberi kesempatan untuk belajar berkhayal, berimajinasi, terutama diberi tuntunan dan latihan dengan laku menulis dalam mengarang ‘bebas’ bersumber pada imajinasi masing-masing siswa. Tak cukup hanya latihan sekali, dua kali, tetapi mesti berkali-kali sebanyak mungkin. Dan ….. guru kami benar-benar guru dalam arti, ia memberi koreksi pada benarnya susunan kalimat dan kekayaan imajinasi dan kreasi dengan tinta merah yang dicoretkan dan digariskan bila keliru. Tak cukup tarikan garis merah saja, namun kalimat-kalimat pembetulan dituliskan! Yang terakhir ini maha penting, lantaran siswa diajari bagaimana mengarang dengan melakukannya. Serta membuat kalimat tulisan ‘baru’ yang benar bila salah. Jadi ini beda antara belajar nulis dengan benar-benar nulis versus talk about writing (bicara, menerangkan lisan tanpa praktek, notabene bisa berlama-lama tanpa latihan). Saya ingat sang guru (kini sudah alm.) menegaskan, kemahiran mengarang itu proses yang harus dimulai dari titik awal SPOK tadi, lalu menulis kalimat-kalimat. Dari kalimat ke kalimat diteruskan menjadi alinea. Apa yang memandu proses menulis ini? Menurut pengalaman saya: logika atau penalaran akal sehat yang juga mesti dilatih dengan disiplin akal budi untuk bila mengarang ada fokusnya, langkah-langkah jalan pikiran lalu penalaran biasa sebab akibat sesederhana mengamati kenyataan sehari-hari, semisal: ada asap pasti ada api! Ada gejala batuk dan masuk angin, tentu harus dicari mengapanya? Karena berhujan-hujan kemarin dulu.
Panduan logika inilah yang menanamkan disiplin berpikir untuk dituangkan dalam bentuk tulisan. Seorang teman dulu bertanya lucu, namun masuk akal, bila penalaran tidak disiplin berfokus dalam lisan (wacana) sehari-hari, apakah dalam tulisan juga kacau? Jawabannya, seratus persen benar! Maka ada panduan ‘orasi’ lisan atau pidato yang mesti pula menuruti disiplin akal sehat dengan bahas membahas saat berlatih bicara dan pidato dalam pelajaran “academia”. Nama ini berasal dari jaman sekolah bertutur, berwacana, berfilsafat sahaja saat Yunani memulai dengan Accademia di sekolah-sekolah Socrates, Plato (Yunani kuno). Proses berdisiplin nalar dengan akal sehat lalu berbicara dengan latihan nalar kejelasan fokus isi pikiran yang kita mau katakan lisan. Diteruskanlah dalam mengkalimatkan ditulisan sehingga isinya masuk akal dalam artinya dipahami dan dimengerti oleh orang lain. Justru pada saat omongan lisan atau tulisan itu bisa dipahami, ditangkap isinya, maksudnya oleh akal sehat orang lain, inilah tulisan atau lisan sebagai proses menyatakan ‘sesuatu’ yang benar (kalimat-kalimatnya runtut secara logika, bisa jelas mana SPOKnya) dan dalam kelisanan dipahami oleh sesama, titik inilah lisan dan tulisan menjadi LITERASI. Kata asli bahas latin literare, itu memberi ‘terang’ atau mudahnya, dari buta huruf menjadi melihat atau melek huruf. Dari “kegelapan’ proses literasi menjadi terang atau cahaya. Dari gelap ketidaktahuan berproses menjadi ‘tahu’ dan paham. Orang Jakarta meneriakkannya sebagai “ngeh”, “gue paham!” Saya ingat teman guru yang setiap selesai 1 bagian pengajaran lalu bertanya keras-keras (suara maksudnya!) ke murid: “Paham?”, “Mengerti?”
Sementara bisa ditarik benang merah yaitu tulisan yang ‘mencerahkan’ itu berproses sebagai literasi. Istilah leterasi menggaung 5 tahun lebih ini, untuk ikut arus pendidikan pengakasaraan (alfabetisasi) yang dulu sudah dijalankan, yaitu: pemberantasan buta huruf menjadi “melek huruf”, alias bisa membaca dan menulis. Literasi ini, bila Anda foto group bersama-sama akan memakai simbol “jari L “ = literasi. Padahal simbol “L” juga bisa dibaca LAWAN, pada jaman perjuangan Wiji Thukul, yang hilang atau dihilangkan sampai kini.
Sebagai proses literasi, maka menulis, mengarang, jelaslah tujuannya yaitu: pertama, membuka mata kenal huruf dan makna aksara sampai tidak hanya bisa baca tulis, namun lebih dari itu membuka cakrawala kesadaran yang dalam bahasa pendidik Paulo Freire, ia namai ‘konsientisasi melalui alfabetisasi’ itu mesti menjadi proses yang membawa perubahan kesadaran (di sini budi atau logika penting) dari “bisu”: tidak mampu berujar, bersuara atau menulis menjadi kesadaran tahap satu, aktif bicara atau nulis, namun masih tanpa fokus atau obyek, namanya kesadaran intransitif untuk dibawa terus melalui literasi ke kesadaran transitif. Maksudnya, mampu menunjuk ke akar masalah, semisal: mengapa hasil ulangan guru A terus buruk dari murid-muridnya, padahal di kelas yang sama, guru lain bisa bagus. Transitifnya menemukan akar obyek soal yaitu, sang guru bila mengajar jalan pikiran berputar-putar sehingga tuturan lisannya “ruwet”. Akibatnya murid tidak paham, tidak terliterasi. Puncak kesadaran pengaksaraan setelah intransitif (tak berobyek) lalu transitif alah transitif “kritis”: murid berani mempertanyakan dan diskusi debat. “Nah, di sini literasi mencapai finalnya bila kesadaran transitif kritis itu membangun, membuat perubahan, alias transformatif. Maksudnya, mendorong daya perbaikan”.
Bila penalaran akal sehat menjadi pandu menulis, maka tinggalah kemauan atau kehendak untuk mau menulis itu menjadi pendorongnya. Sama seperti jaman mandi pagi masih pakai gayung air yang dicedokan ke bak mandi, maka guyuran pertama air dingin meski sejuk itulah yang megawali hari kita, akan segar atau malas bangun dan enggan mandi pagi. Penentu ya guyuran gayung pertama air yang menyirami tubuh kita dengan segar mesti dilakukan! Mulai dan mulai belajar menulis itulah satu-satunya langkah tindakan bila mau mengarang atau menulis. Di jaman digital ini sebenarnya sarana teknologinya amat memperlancar, asal tekad hasrat untuk menulis tadi dihentakkan. Digital dan laptop dan seterusnya, bila keliru tinggal mengoreksi mudah, jaman dulu bila nulis pakai pensil , harus ada penghapus dulu. Pertanyaan akhirnya dalam soal tulis menulis ini adalah bahasa singkat-singkat WA atau SMS, ternyata mencerminkan generasi SMS yang pendek-pendek bila menulis karangan. Bila harus membuat esai, mereka tak dilatih atau tak melatih diri dan dibiasakan untuk menulis kalimat lebih panjang, lebih bernas, berisi dengan latihan, latihan menulis dan menulis terus.
Pengalaman menjadi guru, menunjukkan keterkaitan langsung antara ada tidaknya pembiasaan membaca, lalu latihan membiasakan menulis dan belajar merangkum bacaan menjadi tulisan padat. Saat reading habit (kebiasaan membaca) hanya baca yang disenangi saja dan tidak ditantang untuk yang literatif, (baca: berdampak mencerahkan sebagai literasi), maka makin permukaan pengenalan akan ilmu dan kehidupan yang ada dalam bank literasi. Dulu ada simbol menarik, bila buku seseorang tetap tertutup rapi, tampa coretan atau lipatan sebagai pernah dibaca, maka artinya, ilmu itu tetap tertutup. Kini bila laptop hanya dipakai untuk yang “menyenangkan” dan “games” dan tidak untuk klik intuk pengetahuan, peradaban dan soal-soal essensial hidup, maka sayang sekali laptop itu tak dipakai sebagai alat kerja atau pacul/cangkul yang menggeletak.
Mudji Sutrisno SJ
Budayawan







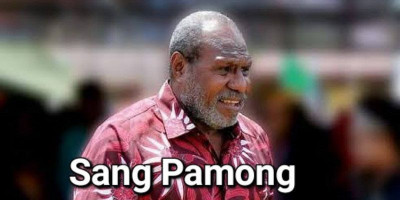






Komentar