Masa Depan Otonomi Daerah Di Indonesia

Oleh: R. Siti Zuhro, Peneliti Ahli Utama BRIN
ASKARA - Akhir-akhir ini banyak sorotan terhadap pelaksanaan otonomi daerah setelah munculnya UU Cipta Kerja dan UU Minerba. Kedua UU ini dinilai publik telah menarik mundur otonomi daerah karena sejumlah urusan yang menjadi kewenangan daerah dikelola langsung pemerintah pusat. Berbagai diskusi terkait otonomi daerah pun sering dilaksanakan, baik oleh kampus maupun pegiat demokrasi dan pemerintah daerah dan bahkan juga lembaga tinggi negara DPD RI.
Menurut pasal 18 (5) UUD NRI 1945 menyebutkan “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”. Ada 6 urusan absolut Pemerintah Pusat: PLN, Pertahanan, Keamanan, Yustisi, Moneter dan Fiskal Nasional, Agama.
Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan memajukan daerah dan menyejahterakan rakyat daerah. Namun, mulai UU 22 Tahun 1999, UU 32 Tahun 2004, sampai UU 23 Tahun 2014 (tentang Pemda) permasalahan menonjol yang acapkali muncul adalah tarik-menarik kewenangan antara Pusat dan Daerah dalam mengelola sumber-sumber yang ada di daerah. Secara umum relasi Pusat-Daerah acapkali tidak harmonis. Hal ini karena adanya ketidakpuasan Daerah kepada Pusat, dan khususnya disebabkan oleh terbatasnya kewenangan yang dimiliki daerah dalam menjalankan otonomi daerah.
Pertanyaan besarnya bagaimana prospek otonomi daerah, khususnya setelah ditetapkannya UU Cipta Kerja dan UU Minerba?
Pelaksanaan Otonomi Daerah (2001-2023)
Evaluasi sejauh ini menunjukkan bahwa pelaksanaan desentralisasi dan Otda belum menggembirakan. Mengapa? Mayoritas pemerintah daerah belum efektif meningkatkan kualitas pelayanan publik, daya saing lokal rendah dan otda belum mampu menyejahterakan masyarakat.
Otonomi daerah cenderung dimaknai sebagai keleluasaan mengelola keuangan dan SDA yang ada di daerah, tapi pengawasan dan akuntabilitas pemda belum memadai. Tak hanya korupsi saja yang marak, tarik-menarik kewenangan pun terus berlanjut antara Pusat dan Daerah.
Isu kewenangan mengedepan dan tarik-menarik kepentingan antara pusat-daerah dan antardaerah dalam mengelola SDA, SDE, SDM tampak, sehingga memunculkan konflik yang lebih menonjolkan ego kedaerahan. Sementara kerjasama antardaerah belum menjadi trend daerah.
Hubungan pusat dan daerah kurang harmonis, daerah-daerah cenderung resisten terhadap (kebijakan) pemerintah pusat. Distrust daerah terhadap pusat acapkali muncul karena kebijakan pusat acapkali berubah-ubah dan merugikan daerah.
Persepsi sepihak daerah tentang kewenangannya yang acapkali lebih mementingkan kepentingan daerahnya sendiri tanpa mempertimbangkan secara sungguh-sungguh manfaatnya dalam konteks yang lebih luas (baik regional maupun nasional) menimbukan kerumitan (hubungan) pengelolaan kewenangan daerah dan antardaerah. Hal ini membuat relasi antara kedaerahan dan keindonesiaan masih negatif, lebih menonjol kedaerahannya.
Praktik otonomi menjadi sangat elitis dan tak menyentuh kebutuhan akar rumput. Otonomi hanya dinikmati oleh kelompok elite saja.
Tantangan krusialnya adalah bagaimana menyelaraskan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar menghasilkan sinergi, koordinasi dan interaksi yang lebih baik antar tingkatan pemerintahan.
Rangkaian implikasi negatif pengelolaan hubungan kewenangan pusat-daerah menghambat proses otonomi daerah.
Munculnya konflik kepentingan di daerah juga menunjukkan kurang memadainya pengelolaan kewenangan daerah dan antardaerah.
Elite lokal di tingkat provinsi dan kabupaten/kota tak mampu membuat program yang saling selaras dan bersinergi (kerjasama) guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Tekad menjalankan desentralisasi dan otonomi daerah belum diikuti oleh kesungguhan, komitmen dan konsistensi yang tinggi semua stakeholders terkait, baik lokal maupun nasional untuk membangun Indonesia dari daerah.
Praktik otonomi yang seharusnya ditopang penuh oleh kepemimpinan daerah yang kuat untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif tak mewujud karena pilkada langsung belum menjadi sarana yang efektif dan efisien bagi daerah untuk merekrut pemimpin yang amanah yang memajukan daerah dan masyarakatnya.
Besarnya kesenjangan ekonomi/politik antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur, dan antara wilayah Jawa dan luar Jawa, serta masih banyaknya jumlah daerah-daerah tertinggal telah menghambat pembangunan nasional.
Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan yang diserahkan ke daerah tidak efektif, membuat daerah-daerah acapkali kehilangan kendali.
Selain itu, adanya perbedaan persepsi antara pusat dan daerah mengenai desentralisasi dan otonomi daerah dalam konteks NKRI (kedaerahan dan keindonesiaan) membuat pusat dan daerah seolah jalan masing-masing.
Omnibus Law Ciptaker dan Dampaknya terhadap Otonomi Daerah
Omnibus Law Ciptaker merupakan kumpulan berbagai UU, termasuk terkait otonomi daerah. UU ini intinya mengatur pengelolaan kewenangan dan pengawasannya. Yaitu tentang siapa melakukan apa, siapa berperan apa, bagaimana itu dilakukan dan seperti apa bentuk pertangungjawabannya.
Salah satu contohnya, perubahan yang krusial terkait pemindahan perizinan dan pengawasan dari pemerintah daerah kepada pusat, apakah ini akan lebih efektif dan efisien serta memberikan kemanfaatan yang luas bagi rakyat.
Bagi Pemda, perpindahan kewenangan tersebut bisa menimbulkan berbagai risiko seperti hilangnya pendapatan daerah hingga kemungkinan kerusakan lingkungan karena tiadanya pengawasan pemda terhadap kegiatan pertambangan di daerah.
UUD NRI 1945 Pasal 18 (5) “Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”.
UU Cipta Kerja jelas menunjukkan bahwa kewenangan Presiden atas seluruh aspek pemerintahan akan semakin absolut. Dalam Pasal 166 yang secara keseluruhan merevisi UU No. 23/2014 hingga UU No. 9/2015 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah mengusulkan untuk merevisi pasal 251 dari UU Pemda.
Pasal 251 versi UU Cipta Kerja, disebutkan bahwa Perda provinsi hingga Perda kabupaten/kota serta peraturan kepala daerah mulai dari provinsi hingga kabupaten dan kota dapat dibatalkan apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Peraturan-peraturan pada level daerah tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku langsung melalui Peraturan Presiden (Perpres). Jika Pemda masih bersikukuh memberlakukan peraturan yang telah dibatalkan melalui Perpres oleh presiden, Pemda bisa dikenai sanksi administratif dan sanksi penundaan evaluasi rancangan Perda.
Sanksi administratif yang dimaksud yakni tidak dibayarkannya hak keuangan kepala daerah dan anggota DPRD selama tiga bulan.
Secara historis, klausul sejenis sudah pernah tertuang dalam UU Pemda dalam pasal yang sama yakni Pasal 251. Dulu, Perda povinsi dan peraturan gubernur yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dicabut secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri.
Apabila terdapat Perda kabupaten/kota ataupun peraturan kepala daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka Gubernur setempat selaku perwakilan pemerintah pusat yang berhak membatalkan Perda tersebut.
Ketentuan-ketentuan tersebut pada akhirnya dibatalkan oleh dua Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yakni Putusan No. 137/PUUXIII/2015 dan Putusan No. 66/PUU-XIV/2016.
Menurut MK, kewenangan Menteri Dalam Negeri ataupun Gubernur untuk mencabut Perda dan Peraturan Kepala Daerah adalah inkonstitusional dan bertentangan dengan Pasal 18 Ayat 6 (pemda berhak menetapkan perda dan peraturan2 lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan), Pasal 28D Ayat 1 (setiap org berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum), dan Pasal 24A Ayat 1 UUD 1945 (MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU thd UU, dan mempunyai nwewenang lainnya yang diberikan oleh UU).
Dengan adanya dua putusan tersebut, Mahkamah Agung (MA) menjadi institusi tunggal yang berwenang untuk membatalkan peraturan daerah baik Perda maupun Peraturan Kepala Daerah. Artinya, pemerintah pusat kembali menghidupkan pasal yang telah dibatalkan oleh MK pada 2015 dan 2016 lalu.
PERIZINAN
Hal yang sama juga muncul dari sisi perizinan. Melalui UU Cipta Kerja, pemerintah merevisi Pasal 350 dari UU Pemda dan dalam pasal terbaru dituangkan bahwa pelayanan berizinan berusaha wajib menggunakan sistem perizinan elektronik yang dikelola oleh pemerintah pusat.
Kepala daerah hanya diberi kewenangan untuk mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan sistem perizinan berusaha sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah pusat. Akan ada sanksi kepada pemda yang enggan melaksanakan ketentuan tersebut.
Pemerintah pusat dapat mengambil alih kewenangan perizinan berusaha dari gubernur bila teguran tertulis dari pemerintah pusat (dua kali berturut-turut) tidak diindahkan oleh kepala daerah. Gubernur juga diberi kewenangan untuk mengambil alih kewenangan perizinan berusaha dari bupati/wali kota.
Pasal 402A yang ditambahkan dalam UU Cipta Kerja menyatakan bahwa pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dengan pemda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Cipta Kerja. Pasal ini masih kabur karena tidak ada penjelasan mengenai klausul baru dari Pasal 402A tersebut.
Seiring dengan tergerusnya kewenangan pemerintah daerah, kewenangan pemerintah pusat pun makin absolut diperkuat dengan klausul-klausul baru dari UU Cipta Kerja.
Pada Pasal 164, tertulis jelas bahwa dengan berlakunya UU Cipta Kerja, maka kewenangan menteri, kepala lembaga, ataupun pemda yang telah ditetapkan dalam UU Cipta Kerja wajib dimaknai sebagai kewenangan presiden.
Sebagai Contoh, semakin kuatnya kewenangan pemerintah pusat atas urusan daerah adalah terkait penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Dalam Pasal 15 UU Cipta Kerja, disebutkan bahwa pemda wajib menyusun RDTR digital sesuai dengan standar dan pemerintah pusat pun wajib mengintegrasikan RDTR dalam bentuk digital ke dalam sistem perizinan berusaha secara elektronik.
Apabila pemda belum menyusun RDTR, maka pelaku usaha dapat mengajukan perizinan pemanfaatan ruang kepada pemerintah pusat dan pemerintah pusat pun bisa menyetujui kegiatan tersebut sesuai dengan rencana tata ruang.
Dalam revisi atas UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang, bupati dan walikota wajib menetapkan peraturan kepala daerah tentang RDTR paling lama 1 bulan setelah RDTR yang dimaksud telah disetujui subtansinya oleh pemerintah pusat.
Jika dalam waktu satu bulan tidak segera ditetapkan, maka RDTR dapat ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat.
UU Minerba
Melalui UU 3/2020 kewenangan pemerintah daerah tersebut dicabut. Sedikitnya terdapat 15 pasal yang mengalihkan kewenangan daerah kepada pemerintah pusat.
Pengelolaan natural resource akan cenderung sentralistik. Pemda tidak memiliki posisi tawar dan tidak terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam. Hal ini bisa membuat Pemprov bisa jadi tak lagi merasa memiliki atau tak peduli terhadap natural resource dan juga terkait dampaknya terhadap lingkungan.Menurut UU 3/2020 Pasal 35 Ayat 4, daerah mengelola IPR (izin pertambangan rakyat) dan SIPB (surat izin pertambangan batuan). Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2020 “Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Minerba.
Dengan kata lain, dari perspektif otonomi daerah, UU Minerba yang baru ini menandai ditariknya kembali urusan yang menjadi kewenangan daerah, baik dari aspek perizinan maupun pengawasan. Dengan alasan ingin menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, pemerintah pusat mengambil kewenangan daerah dalam mengelola mineral dan batu bara.
Pertanyaannya, apakah pemerintah pusat mampu mengelola proses perizinan dan pengawasan wilayah pertambangan di seluruh Indonesia? Bagaimana tanggung jawab sosial pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang tak ada lagi dalam UU Nomor 3 Tahun 2020?.
Dari uraian tersebut di atas jelas kiranya bahwa materi muatan dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja telah nyata-nyata mereduksi hak otonomi seluas-luasnya yang diberikan kepada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten berdasarkan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Seperti pemangkasan beberapa kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota), di antaranya, sebagai berikut: Hilangnya kewenangan memproses dan menerbitkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal) dan izin lingkungan (Pasal 22). Hilangnya konsultasi penentuan wilayah potensial minyak dan gas bumi (Pasal 40). Dipangkasnya kewenangan ketenagalistrikan (Pasal 42). Hilangnya kewenangan memberikan persetujuan kawasan ekonomi khusus (Pasal 150).
Materi muatan dalam UU Cipta Kerja menguatkan pola yang mengarah pada kesimpulan terjadinya praktik resentralisasi kekuasaan. Pola tersebut terbentuk dengan lahirnya undang-undang yang memiliki pengaturan seperti penarikan urusan dari pemerintah daerah dan instrumen persetujuan atau evaluasi oleh pemerintah pusat yang semakin ketat. Praktik resentralisasi ini sejatinya telah melanggar original intens yang melahirkan ketentuan dalam konstitusi yang menyatakan bahwa otonomi seluas-luasnya dimiliki oleh pemerintah daerah.
Penutup
Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sama-sama mengemban dan melaksanakan amanat mewujudkan tujuan/kepentingan nasional, yaitu mencerdaskan dan menyejahterakan rakyat. Belum satunya persepsi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi membuat mereka seolah jalan sendiri-sendiri. Hal ini menimbulkan ketidakpastian. Minimnya koordinasi, pembinaan dan pengawasan (korbinwas) berpengaruh negatif terhadap pola relasi pusat-daerah dan juga terhadap kenerja Pemda.
Secara ketatanegaraan kebijakan otonomi daerah merupakan “big bang” bagi Indonesia, tapi pada saat yang sama juga lebih mengesankan praktik yang cenderung “too much too soon”. Di tataran empirik sejauh ini menunjukkan bahwa perubahan-perubahan besar yang tidak diikuti komitmen yang cukup di bidang penegakan hukum justru malah merugikan. Bila hal itu tidak dibenahi secara serius, akan mengancam keutuhan Indonesia. Komitmen kepala daerah dan penegakan hukum sangat penting untuk menopang keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.
Resistensi sejumlah kepala daerah dan ketua DPRD terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja perlu dijadikan pertimbangan serius pemerintah pusat dalam menerapkan UU 3/2020 yang dalam banyak hal selaras dengan UU Omnibus Law UU Ciptaker, khususnya terkait otonomi daerah. Bagi daerah, hal tersebut merupakan kebijakan sentralisasi kekuasaan. Pengalaman sejarah pemberontakan daerah 1958 harus menjadi pelajaran berharga bahwa ketidakpuasan dan kekecewaan daerah baik secara ekonomi maupun politik dan atau ketidak adilan tak hanya mengancam stabilitas/keamanan politik, tapi juga mengancam integrasi nasional. Keutuhan NKRI menjadi taruhannya.




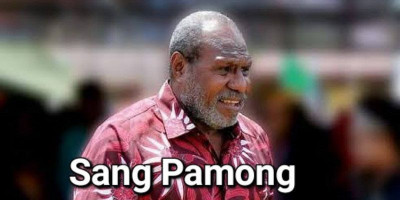






Komentar