Tak Ada Alat Konstitusi untuk Mereview Produk Putusan MK

ASKARA - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang ketentuan tambahan pengalaman menjabat dari keterpilihan pemilu dalam syarat usia minimal Calon Presiden atau Calon Wakil presiden telah menimbulkan polemik.
Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi pun akhirnya membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) guna mengurai persoalan laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang ditujukan kepada Ketua MK Anwar Usman.
Merespon hal itu, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia Dr. Fahri Bachmid, S.H.,M.H. Memberikan pandangan serta analisis hukumnya,
Fahri Bachmid berpendapat bahwa Sebenarnya jika ditelaah lebih jauh secara cermat, baik dari aspek filosofis maupun legalistik, tidak cukup terdapat argumentasi yang memadai untuk dengan mudah menjustifikasi bahwa produk putusan dari lembaga Etik dapat membatalkan produk putusan mahkamah konstitusi (MK).
Sebab pada hakikatnya MK dengan putusannya adalah organ konstitusional yang sangat limitatif terkait dengan kewenangan atributifnya, termasuk sifat putusannya yang bercorak "ergo omnes" maupun "final and binding".
"Dengan demikian sepanjang mengenai produk putusan yang telah dikeluarkannya, sama sekali tidak dibuatkan sebuah mekanisme banding atau peninjauan kembali untuk mereview terhadap segala hal, baik materil maupun formil yang melingkupinya," ujar Fahri Bachmid di Jakarta, Senin (06/11/2023).
"Apakah yang berkaitan dengan keadaan atau fakta hukum tertentu, aspek legal serta prosedur hukum acara dan seterusnya, tidak terkecuali unsur dinamika yang terjadi dalam proses pengambilan putusan dalam forum rapat permusyawaratan hakim (RPH)," sambunf Fahri Bachmid.
Fahri Bachmid menegaskan, jika dalam suatu putusan di persidangan terdapat pendapat berbeda "dissenting opinion" dan atau alasan hukum yang berbeda "concurring opinion" para hakim konstitusi, maka putusan tersebut tetap berlaku.
"Tetapi ketika telah dibacakan dalam forum persidangan yang terbuka untuk umum, maka tentunya disitulah letak keabsahan atau keberlakuannya, apakah sifatnya putusan MK yang "Self Implementing", atau "Legally Null And Void"atau "Conditionally Constitutional" ataukah yang "Conditionally Unconstitutional" dan seterusnya," tegas dia.
Dengan kata lain, tegas Fahri Bachmid, setelah putusan itu diketok, maka tidak tersedia lagi alat konstitusional untuk dapat mengujinya.
"Hal ini tentunya berbeda yang konstruksi pelembagaan forum etik MK, yang cuman berdasarkan pada mandat hukum setingkat Undang-undang, yang mana Undang-undang mendelegasikan agar MK wajib menyusun Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang berisi norma yang harus dipatuhi oleh setiap hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan," kata dia.
Sehingga jika mencoba mendalami dengan metode penafsiran yang sistematis serta teleologis, maka sesungguhnya produk putusan MKMK dalam hal Hakim Terlapor atau Hakim Terduga, menurut Majelis Kehormatan, jika terbukti melakukan pelanggaran, maka konsekwensi hukumnya adalah diberikan sanksi, baik ringan maupun berat.
Karena itu, sangat sulit untuk menalar jika putusan etik dapat menganulir putusan pengadilan.
"Saya belum menemukan suatu argumentasi konstitusional dan hukum yang kokoh terkait dangan ekstensifikasi produk putusan lembaga etik yang dapat membatalkan produk putusan MK, belum memadainya teori serta doktrin hukum yang relevan dangan hal itu," kata Fahri Bachmid.
Fahri Bachmid menjelaskan, secara filosofis, sesungguhnya putusan MKMK adalah dalam rangka menegakan "Code of Conduct" yaitu menegakan "Sapta Karsa Hutama" sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentanf pemberlakuan deklarasi kode etik dan perilaku hakim Konstitusi MK RI.
Adanya pandangan dari sebagian pihak yang mempersoalkan Putusan MK telah melanggar ketentuan norma Pasal 17 ayat (5) dan (6) UU RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur bahwa "Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara"
Kemudian ketentuan ayat (6) mengatur bahwa "Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan"
Fahri Bachmid berpendapat bahwa masih terdapat kekosongan pengaturan terkait pranata tersebut.
Oleh karena mekanisme teknis terkait dengan bagaimana MK mengadili ulang perkara yang terkategori terdapat pelanggaran prosedur mengadili oleh karena terdapat dugaan "conflict of interest" dalam perkara tersebut, sebab UU MK tidak mengatur jalan keluar secara yuridis jika keadaan hukum yang demikian itu memang terjadi.
Sebab hal tersebut secara ideal harus diatur dalam undang-undang organik yang mengatur secara khusus dengan hukum acaranya dalam UU 24 tahun 2003 tentang MK, dan yang terahir diatur dalam UU No. 7/2020.
Selain tidak diatur dalam UU MK, secara khusus juga tidak diatur dalam peraturan mahkamah konstitusi terkait dengan pranata konstitusional itu.
"Sehingga saya berpandangan memang masih terdapat kekosongan hukum "recht vacuum" atas persoalan itu, idealnya norma tersebut dapat diatur secara khusus sebagai ketentuan derivatif langsung dari UU kekuasaan kehakiman, sehingga rumusan lebih lanjut diatur dalam UU MK atau peraturan mahkamah konstitusi, dengan demikian bangunan norma menjadi jelas dan terang," tutup Fahri Bachmid.


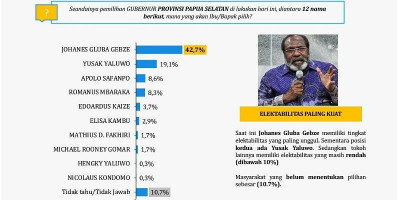








Komentar