OPINI
Memahami Supermasi Hukum

Oleh: Muchyar Yara *
ASKARA - Sudah sejak lama sekali kalangan hukum di negeri ini mengidam-idamkan terwujudnya “supremasi hukum”. Ketika pelita V sedang digodok oleh BP-MPR, ada usulan agar supremasi hukum ditetapkan sebagai prioritas pembangunan nasional, untuk menggantikan pembangunan ekonomi yang sejak pelita pertama menempati prioritas pembangunan nasional, namun akhirnya upaya ini gagal, bahkan ketika MPR kemudian menetapkan pembangunan jangka panjang tahap II, ekonomi tetap menjadi prioritas pembangunan nasional.
Menyusul terjadinya krisis moneter/krisis ekonomi dan kemudian berkembang menjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah/presiden, maka lahirnya Orde Reformasi menggantikan posisi Orde Baru. Pada awal Orde Reformasi kehidupan masyarakat masih tidak menentu, seluruh sendi-sendi dan aspek kehidupan sosial mengalami dis-harmonisasi, termasuk juga tentunya aspek kehidupan hukum (sebagai salah satu “social institution”/Lembaga Sosial yang bekerja di tengah-tengah masyarakat), mengalami degradasi fungsi dan apresiasi di setiap sendinya.
Di tengah situasi “social disorder” dewasa itu, muncul kembali harapan terhadap “supremasi hukum”, di mana diharapkan dengan “supremasi hukum” akan tercipta “social order” atau setidak-tidaknya dapat mengendalikan “social disorder” serta kemudian mengarahkannya menjadi “social order”. Harapan ini pada satu sisi merupakan kehormatan besar bagi kalangan hukum, tetapi pada pihak lainnya juga merupakan tanggung jawab yang teramat besar.
Hukum adalah salah satu lembaga sosial (social institution) di samping lembaga-lembaga sosial lainnya, seperti ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya dan sebagainya. Lembaga-lembaga sosial ini hidup dan saling bekerja sama di tengah suatu masyarakat. Sebuah institusi sosial baru bisa secara effektif berperan sebagai faktor pengubah masyarakat (pemegang Supremasi), bilamana institusi sosial tersebut menempati posisi sebagai “primary social institution” atau menjadi Lembaga sosial yang terpenting/tertinggi (memegang supremasi) serta menjadi acuan/anutan segenap Lembaga Sosial lainnya yang bekerja ditengah masyarakat yang bersangkutan. Apa yang ditetapkan oleh Lembaga pemegang supremasi tersebut akan diikuti atau mempengaruhi lembaga-lembaga sosial lainnya yang ada di masyarakat yang bersangkutan.
Berkaitan dengan harapan di atas agar hukum menmpati posisi supremasi perlu kiranya terlebih dahulu dijelaskan, bahwa:
1. harapan terhadap “supremasi hukum” sesungguhnya mengandung unsur “unfair”, artinya harapan termaksud bukanlah suatu kehormatan ataupun tanggungjawab, melainkan suatu pembebanan yang tidak fair. ketika situasi sosial sudah terlanjur “kacau-balau”, kemudian “hukum” didorong kedepan untuk menyelesaikannya. Padahal “hukum” bukanlah faktor signifikan yang menyebabkan timbulnya “social disorder” tersebut, dan jika diteliti ke belakang akan nampak bahwa justru sektor kekuasaan dan sektor ekonomi yang menjadi penyumbang terbesar terjadinya kritis awal di negeri ini yang kemudian berkembang menjadi krisis yang multi dimensional alias “social disorder”.
2. Untuk bekerjanya hukum di-tengah-tengah masyarakat diperlukan adanya “preconditions” (prasyarat), di mana preconditions ini pula sekaligus (diantaranya) menjadi “batas-batas kemampuan hukum” atau “keterbatasan hukum” (“the limits of law”). Contohnya yang sederhana, hukum tidak bisa bekerja secara baik di tengah situasi chaos. Situasi chaos hanya mungkin diatasi oleh kekuatan phisik yang lebih besar dari situasi chaos termaksud (physical anti-chaos power). Contohnya yang moderat, hukum tidak bisa bekerja secara baik bilamana apresiasi warga masyarakatnya (tempat hukum itu bekerja) terhadap hukum berada pada peringkat yang rendah. Untuk itu harus terlebih dahulu diubah pandangan masyarakatnya terhadap hukum agar menjadi positif, dan ini merupakan wilayah garapan ilmu budaya, khususnya ilmu budaya hukum (legal culture), yang berada di luar wilayah ilmu dogmatik hukum.
Menurut sosiologi, sebuah institusi sosial baru bisa menempati posisi supremasi, sehingga secara effektif mampu berperan sebagai faktor pengubah masyarakat, bilamana institusi sosial tersebut menempati posisi sebagai “primary social institution” atau menjadi lembaga sosial yang terpenting/tertinggi serta menjadi acuan/anutan segenap lembaga sosial yang bekerja di tengah masyarakat yang bersangkutan.
Nampaknya pada waktu itu (awal era reformasi) lembaga sosial “kekuasaan/politik” atau institusi sosial “ekonomi” salah satunya masih menempati posisi sebagai “the most primary social institusi” dikalangan masyarakat indonesia. Tambahan lagi lembaga Politik sedang mengalami eforia pada waktu itu setelah selama puluhan tahun dibelenggu oleh Orde Baru.
3. Agar hukum dapat bekerja secara normal atau wajar saja (bukan bekerja pada tingkatan supremasi), artinya di sini hukum hanya dapat berperan sebagai “faktor pengendali sosial” (belum sebagai “faktor pengubah sosial), dibutuhkan persyaratan-persyaratan yaitu secara “internal” maupun secara “external”.
Persyaratan internal meliputi :
a). kondisi norma hukum positifnya:
Antara lain:
1. Aturan-aturan hukum selaras dengan tingkat kebutuhan masyarakat dan tidak ketinggalan jaman. (hukum pidana saja masih dari jaman kolonial).
Aturan-aturan hukum mampu mengisi kekosongan yang timbul akibat perkembangan jaman (hukum dibidang ekonomi masih jauh tertinggal dari kebutuhan yang nyata).
2. Aturan-aturan hukum positifnya tidak tumpang-tindih., dan sebagainya.
b). Kondisi aparat penegak hukumnya.
“Laws in the books sometimes different with the laws in action”, kenapa? Karena hukum itu tidak bisa bergerak/bekerja dengan sendirinya. Untuk bekerjanya hukum dibutuhkan manusia untuk menggerakannya, mereka inilah para aparat penegak hukum, jika kualitas aparat penegak hukumnya rendah maka bisa terjadi hukum yang hidup di tengah masyarakat menjadi berbeda dengan hukum yang tertulis di kitab-kitab hukum. (tidak perlu dikomentari lagi kondisi aparatur penegak hukum di indonesia saat ini, karena anda pasti lebih paham daripada saya).
c). Kondisi prasarana hukumnya.
Singkatnya, karena hukum itu digerakan oleh manusia, dan setiap manusia tunduk pada hukum-hukum ekonomi, maka untuk bekerjanya hukum di tengah masyarakat diperlukan uang untuk ongkosnya.
Pengalaman menunjukan bahwa anggaran nasional untuk pembangunan/penegakan hukum jumlahnya relatif kecil, dibandingkan dengan mata anggaran lainnya.
Persyaratan external, meliputi antara lain :
a). Kondisi budaya hukum masyarakat yang kondusif.
b). Kondisi ilmu-ilmu pengetahuan pembantu hukum, seperti, sosiologi hukum, kriminologi, bahasa hukum, ekonomi hukum, semiotik hukum dsb, telah berkembang sejalan dengan kemajuan masyarakat.
Semiotik hukum adalah ilmu pengetahuan baru pembantu ilmu hukum yang mengkaji tanda-tanda sebagai norma hukum.
c). Kondisi sosial secara umum yang positif.
Saya tidak menguraikan lebih lanjut persyarataan external ini, karena akan menjadi sangat panjang, tetapi intinya di sini pun kondisinya secara umum belum kondusif.
Berdasarkan uraian di atas, kini saatnya saya mencoba untuk menjawab pertanyaan di atas tentang supremasi hukum.
Meletakan harapan kepada hukum untuk menyelesaian masalah-masalah yang ada di masyarakat dewasa ini melalui memberikan posisi supremasi kepada hukum, ternyata bukan saja “unfair” tetapi bahkan “tidak masuk diakal” karena dengan kondisi internal dan external yang ada, jangankan untuk mencapai tingkat supremasi hukum, sedangkan untuk mencapai tingkatan “penegakan hukum yang wajar” saja, padahal situasi/kondisi sosialnya sudah relatif lebih tenang dibandingkan dengan situasi sosial di awal era reformasi, itupun masih sulit untuk diwujudkan.
Kesimpulan
Pernyataan tentang “supremasi hukum” yang ada dewasa ini adalah merupakan “pernyataan yang bersifat politis” dan bukan merupakan “pernyataan yang bersifat yuridis”.
Sekian
18 Maret 2023
* Mantan Pengajar Sejarah Hukum
Dan Teori Hukum
Bidang Studi Ilmu Hukum
Program Pascasarjana UI dan
Universitas Jayabaya-Jakarta


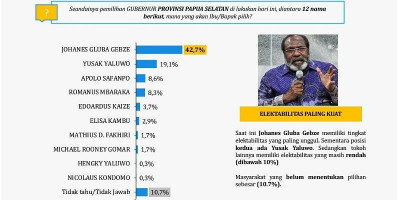








Komentar